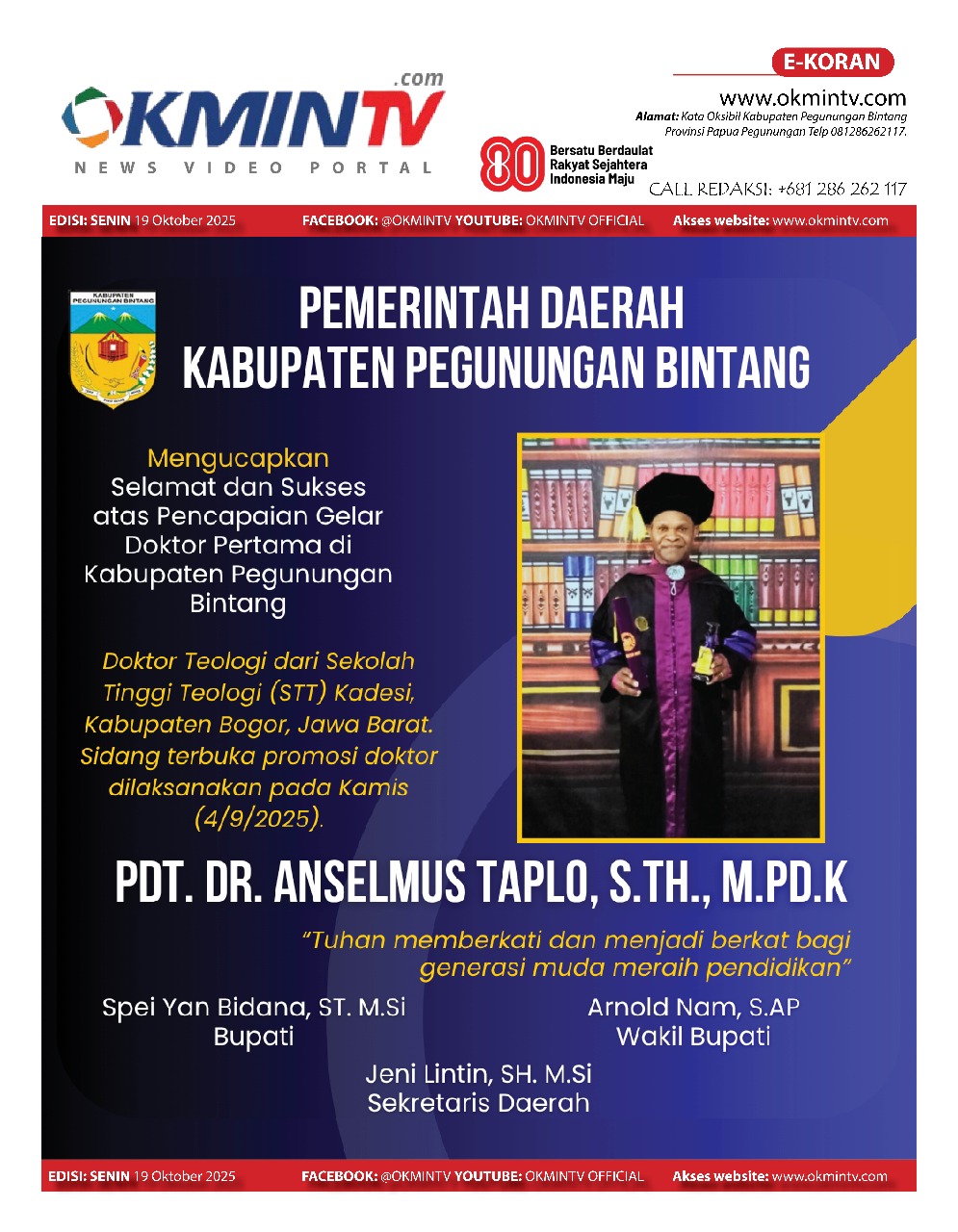Oleh: Prof. Idrus Al-Hamid (Suara Minor Poros Intim)
Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam tata kelola Otonomi Khusus di Papua. Di atas kertas, kehadiran lembaga ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengevaluasi percepatan pembangunan di enam provinsi Papua Raya. Sebuah langkah yang, secara normatif, tampak progresif.
Namun dalam perspektif Hukum Tata Pemerintahan, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah lembaga ini sah dibentuk, melainkan: apakah kehadirannya memperkuat otonomi, atau justru menciptakan potensi dualisme kekuasaan?
Otonomi Khusus dan Mandat Konstitusional
Otonomi Khusus Papua bukan kebijakan biasa. Ia adalah keputusan politik hukum negara untuk menjawab sejarah panjang ketimpangan, marginalisasi, dan ketidakadilan pembangunan. UU Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan bahwa Otsus bertujuan mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), serta memperkuat integrasi NKRI.
Artinya, percepatan pembangunan sudah menjadi mandat normatif kepala daerah, terutama gubernur, yang diberi kewenangan luas dalam pengelolaan Dana Otsus, kebijakan afirmasi, dan perencanaan pembangunan berbasis kekhususan.
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah adalah penyelenggara pemerintahan, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, serta penanggung jawab utama pelaksanaan RPJMD dan APBD. Gubernur bahkan memiliki posisi ganda: kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat.
Kewenangan ini bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang. Maka secara prinsip hukum administrasi negara, kewenangan tersebut tidak dapat dikurangi atau diambil alih oleh organ lain tanpa dasar undang-undang yang tegas.
Di sinilah titik sensitif KEPP Otsus Papua. Koordinasi atau Pengambilalihan?
Secara konseptual, fungsi koordinasi adalah hal yang lazim dalam sistem presidensial. Presiden berwenang membentuk lembaga nonstruktural sebagai instrumen kebijakan. Namun, dalam praktik tata pemerintahan, batas antara koordinasi dan pengendalian sering kali tipis.
Jika KEPP hanya mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian yang selama ini terfragmentasi, maka ia adalah solusi. Tetapi jika ia menentukan prioritas pembangunan, mengarahkan distribusi anggaran, atau mengevaluasi kinerja gubernur secara substantif, maka muncul persoalan konstitusional.
Sebab kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Ia memiliki legitimasi politik yang tidak dimiliki lembaga nonstruktural bentukan eksekutif pusat. Dalam negara demokrasi, legitimasi elektoral bukan perkara sepele. Ia adalah sumber pertanggungjawaban publik.
Apabila keputusan strategis pembangunan Papua bergeser dari gubernur kepada komite yang tidak memiliki mandat rakyat, maka secara teoritik kita berhadapan dengan apa yang bisa disebut sebagai “executive shadow governance” tata kelola bayangan yang bekerja di luar struktur otonomi formal.
Papua dan Problem Implementasi
Harus diakui, persoalan utama Otsus Papua bukan kekurangan regulasi. Dana Otsus telah mengalir dalam jumlah besar. Struktur kewenangan telah diatur. Masalahnya terletak pada efektivitas implementasi, lemahnya pengawasan, dan disharmoni kebijakan pusat.
Banyak program kementerian berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi dengan perencanaan daerah. Akibatnya, pembangunan terasa sporadis dan tidak konsisten. Dalam konteks inilah KEPP bisa menjadi instrumen penyelaras kebijakan pusat.
Tetapi penyelarasan kebijakan pusat berbeda dengan pengawasan terhadap daerah. Jika KEPP difokuskan untuk merapikan koordinasi antar kementerian, maka ia memperkuat gubernur. Namun jika ia menjadi pusat kendali pembangunan, maka otonomi daerah berpotensi tereduksi secara diam-diam.
Otonomi yang direduksi secara administratif sering kali lebih berbahaya daripada sentralisasi terang-terangan, karena ia bergerak dalam ruang abu-abu kewenangan.
Prinsip Subsidiaritas dan Demokrasi Lokal
Dalam teori desentralisasi modern, berlaku prinsip subsidiaritas: urusan yang dapat diselesaikan di tingkat lokal tidak seharusnya ditarik ke pusat. Negara kesatuan bukan berarti semua keputusan harus dikendalikan pusat. Justru stabilitas NKRI diperkuat oleh kejelasan distribusi kewenangan.
Papua adalah wilayah dengan karakter sosial, geografis, dan kultural yang kompleks. Gubernur dan pemerintah daerah lebih memahami konteks lokal dibanding struktur koordinatif pusat.
Jika percepatan pembangunan dilakukan dengan memperkuat kapasitas daerah, maka hasilnya akan lebih berkelanjutan. Namun jika percepatan dilakukan dengan pendekatan komando, risiko resistensi sosial dan delegitimasi politik akan muncul.
Papua tidak hanya membutuhkan percepatan fisik, tetapi percepatan kepercayaan (trust acceleration). Dan kepercayaan lahir dari penghormatan terhadap mandat lokal.
Metafora Tata Kelola
Bayangkan pembangunan Papua sebagai orkestra. Gubernur adalah dirigen yang memimpin irama sesuai partitur RPJMD dan visi politik yang dijanjikan kepada rakyat. Pemerintah pusat adalah produser yang memastikan sumber daya tersedia. KEPP seharusnya menjadi teknisi yang memastikan harmoni suara antar instrumen kementerian.
Masalah muncul jika teknisi naik ke panggung dan mengambil tongkat dirigen.
Percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan arsitektur konstitusional. Sebab ketika kewenangan menjadi kabur, akuntabilitas ikut kabur.
Jalan Tengah: Penguatan, Bukan Penggantian
Solusi bukan membubarkan KEPP, tetapi memperjelas batasnya. Ada beberapa prinsip yang harus dijaga:
Pertama, KEPP harus fokus pada koordinasi kebijakan pusat, bukan intervensi terhadap kewenangan APBD dan RPJMD daerah.
Kedua, setiap evaluasi kinerja daerah harus tetap mengikuti mekanisme formal dalam UU Pemerintahan Daerah.
Ketiga, gubernur harus dilibatkan secara struktural dalam pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar objek koordinasi.
Keempat, transparansi publik harus dijaga agar masyarakat Papua memahami siapa yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan.
Jika prinsip ini dipegang, KEPP bisa menjadi katalisator pembangunan. Tetapi jika diabaikan, ia berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan yang kontraproduktif.
Percepatan Tanpa Menggerus Demokrasi
Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi. Artinya, kekuasaan tidak terpusat secara absolut, tetapi dibagi berdasarkan hukum. Otonomi Khusus Papua adalah bentuk pengakuan terhadap keunikan dan kebutuhan khusus daerah.
Percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan percepatan konsolidasi demokrasi lokal. Tidak boleh ada kesan bahwa pusat lebih tahu segalanya, sementara daerah hanya pelaksana.
Papua membutuhkan kolaborasi, bukan dominasi.
Jika KEPP hadir sebagai jembatan harmonisasi kebijakan, maka ia akan menjadi solusi. Tetapi jika ia menjadi pusat komando baru di atas struktur otonomi, maka kita sedang menciptakan paradoks: mempercepat pembangunan dengan cara memperlambat demokrasi.
Dan dalam negara hukum, demokrasi bukan variabel yang bisa dikorbankan atas nama efisiensi.
Papua membutuhkan percepatan. Tetapi percepatan yang konstitusional. Percepatan yang menghormati mandat rakyat. Percepatan yang memperkuat, bukan menggantikan, kepemimpinan daerah.
Di situlah letak ujian sebenarnya dari KEPP Otsus Papua: menjadi penguat otonomi, atau tanpa disadari menjadi bayangannya.
Tulisan tersebut di atas, sebuah refleksi akademisi, dalam kebingungan Masyarakat terhadap keberadaan Otonomi Khusus dalam kajian strategi Kebijakan Publik Tata Pemerintahan di Papua Raya.
Papua, Februari 2026
By. Si Hitam Manis Pelipur Lara di Timur Nusantara.